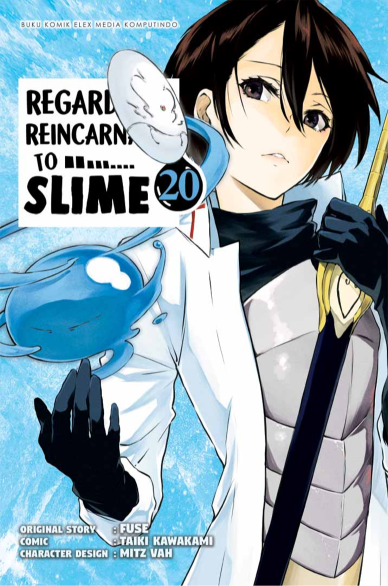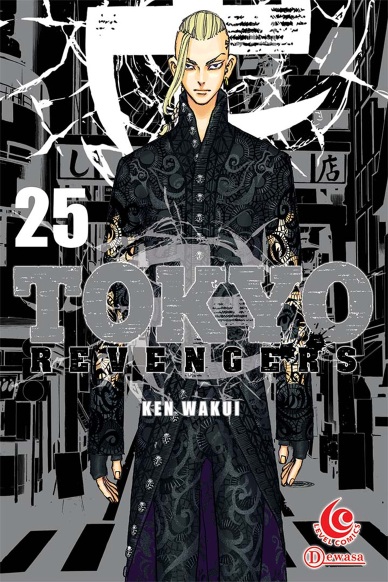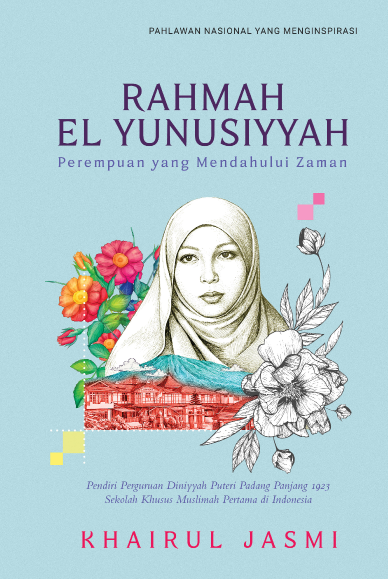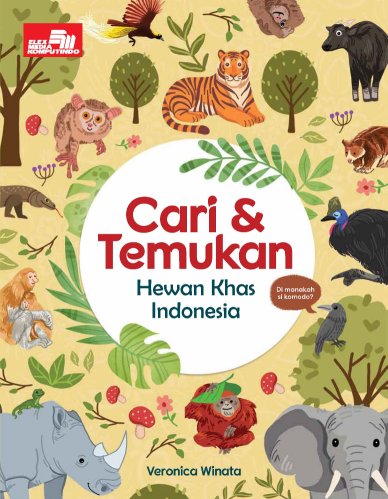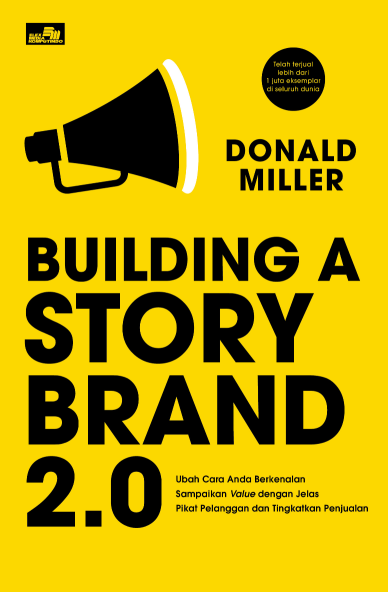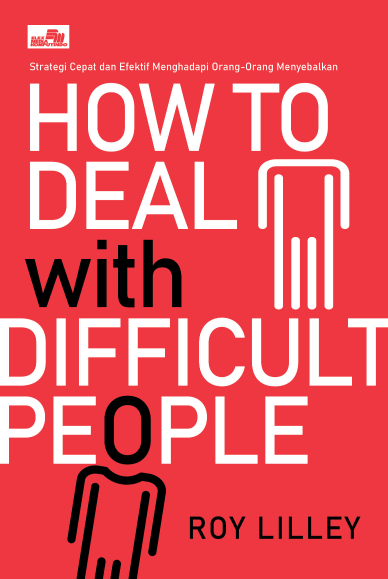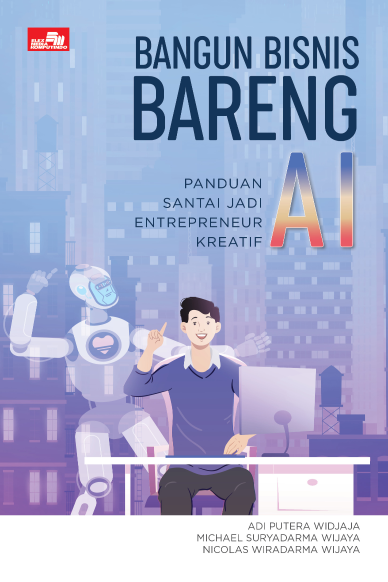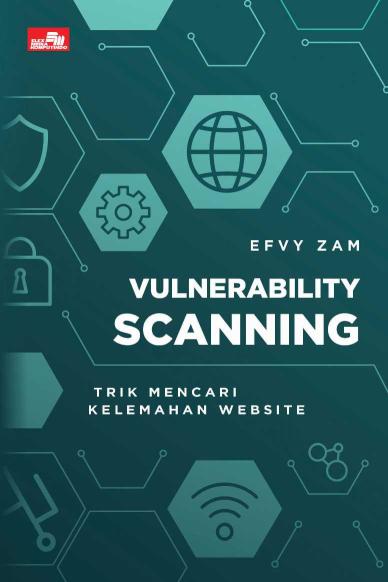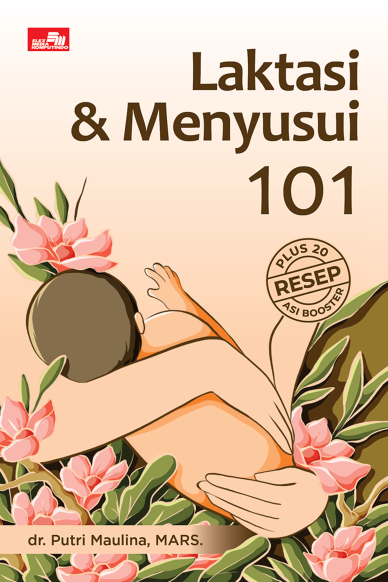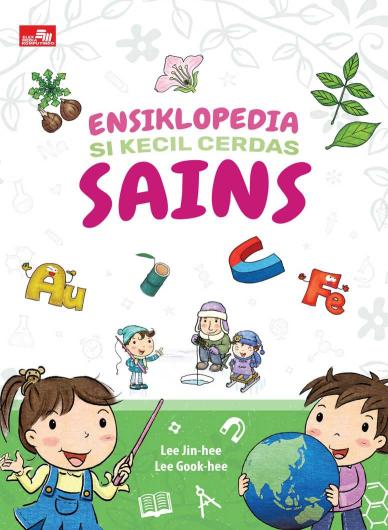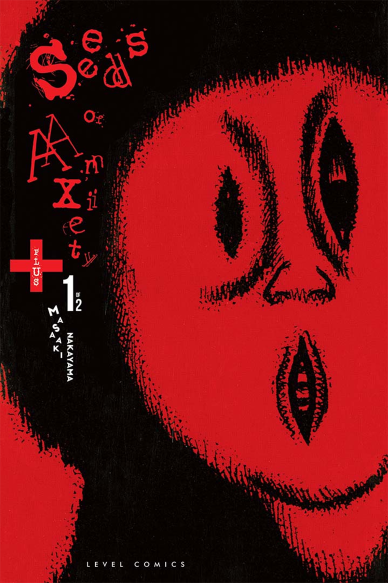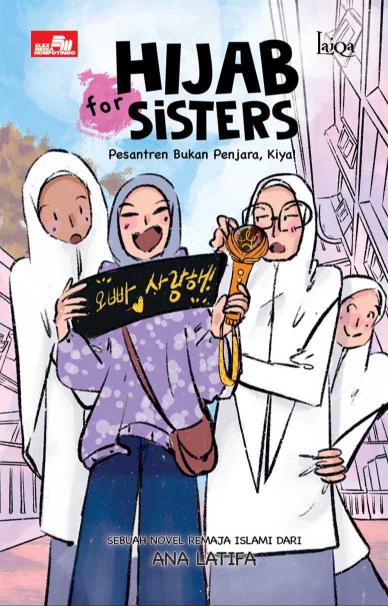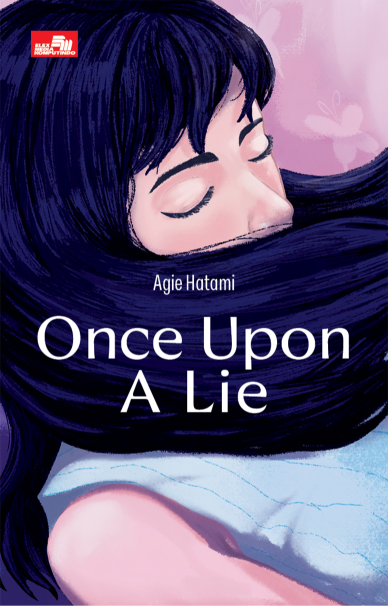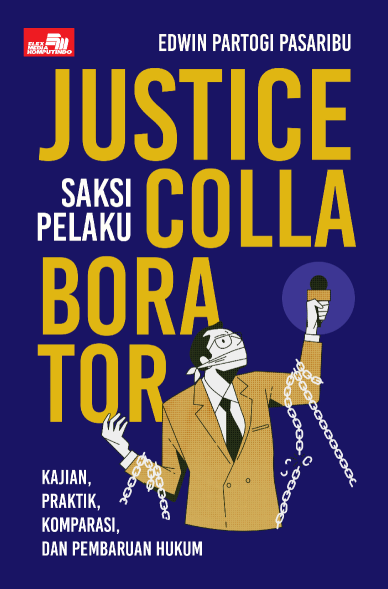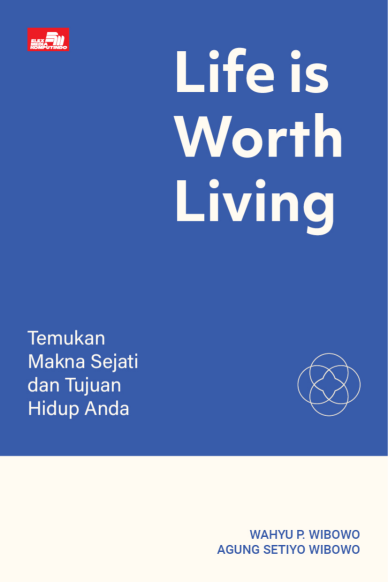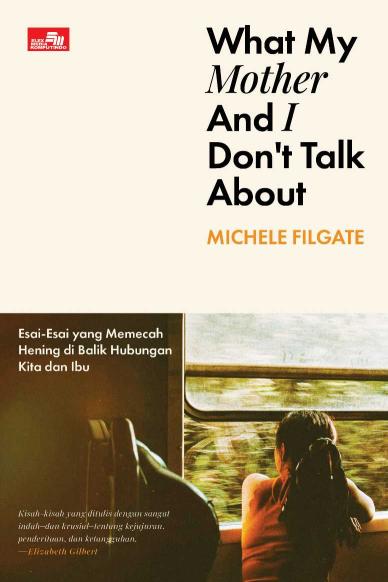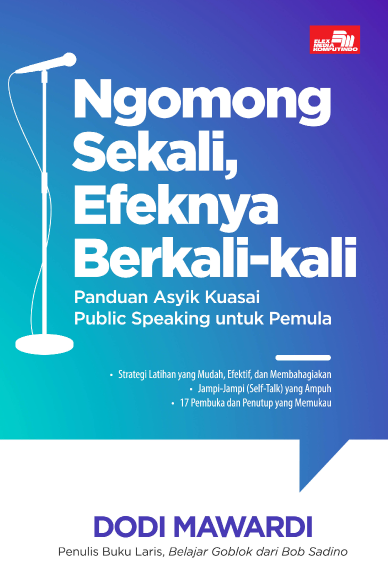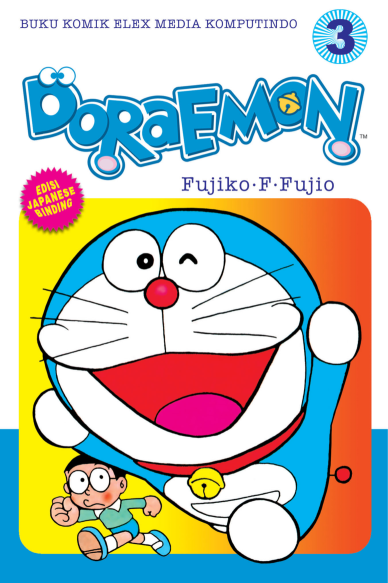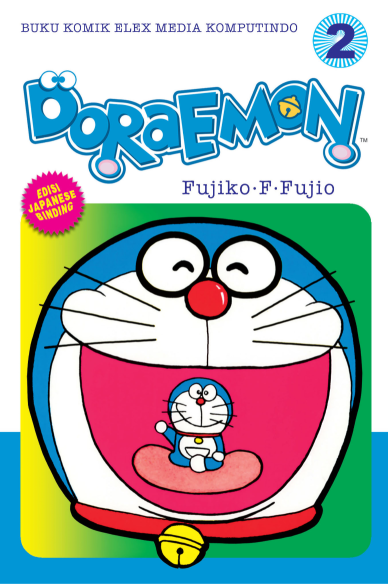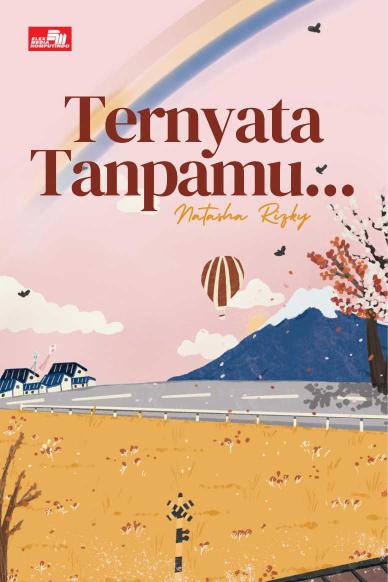Pagi itu, Minggu terasa sedikit berbeda.
Televisi menyala seperti biasa, namun tak ada suara khas Doraemon yang memanggil Nobita. Tak ada kantong ajaib yang terbuka, tak ada baling-baling bambu yang berputar. Slot yang selama puluhan tahun identik dengan satu nama kini terisi program lain. Semua berlangsung normal—terlalu normal—tanpa pengumuman, tanpa pamitan resmi.
Selama lebih dari 35 tahun, Doraemon hadir tanpa perlu diingatkan. Ia selalu ada. Ia menjadi latar bunyi rumah di Minggu pagi, menjadi penanda waktu sebelum aktivitas dimulai, menjadi pengisi ruang antara bangun tidur dan dunia luar yang perlahan menuntut perhatian. Justru karena kehadirannya yang konsisten itulah, kepergiannya terasa ganjil. Doraemon tidak pergi sebagai sebuah peristiwa, melainkan sebagai ketiadaan—dan ketidakhadiran sering kali lebih kuat daripada pengumuman apa pun.
Bagi generasi tertentu, Doraemon bukan hanya tontonan anak-anak. Ia adalah ritual. Minggu pagi memiliki struktur yang hampir sakral: bangun lebih awal, menyalakan televisi, dan menonton bersama—tanpa perlu memilih, tanpa perlu berpindah saluran. Ritual ini membentuk pengalaman kolektif. Anak-anak dari latar belakang sosial berbeda menyaksikan cerita yang sama, pada waktu yang sama, dengan tokoh yang sama. Dalam konteks kebudayaan populer, inilah yang membentuk ingatan bersama—sesuatu yang kini semakin langka di tengah fragmentasi media digital.
Ketika Doraemon berhenti tayang, yang hilang bukan hanya satu program, tetapi satu ritme kehidupan domestik yang perlahan sudah mulai terkikis. Doraemon bekerja dengan cara yang halus. Ceritanya sederhana, konfliknya kecil, dan resolusinya sering kali tidak sempurna. Nobita jarang benar-benar berubah secara drastis. Kesalahan kerap terulang. Alat ajaib hampir selalu membawa konsekuensi. Justru di situlah kekuatannya. Doraemon tidak menawarkan fantasi kemenangan mutlak. Ia menunjukkan bahwa kemudahan sering kali berujung masalah, bahwa tanggung jawab tidak bisa dihindari, dan bahwa pertumbuhan membutuhkan kegagalan.
Kepergian Doraemon dari televisi tidak bisa dilepaskan dari perubahan lanskap media. Televisi tidak lagi menjadi pusat perhatian keluarga. Ia bersaing dengan gawai pribadi, layanan streaming, dan algoritma yang menyajikan konten berbeda untuk setiap individu. Dulu, satu tayangan bisa menyatukan seluruh rumah. Hari ini, setiap orang membawa layarnya sendiri. Konsumsi media menjadi personal, terpisah, dan sunyi—bahkan ketika dilakukan bersama.
Doraemon masih ada. Ia masih tayang di Jepang. Ia masih hidup dalam film, merchandise, dan arsip digital. Namun pengalaman menontonnya di televisi Indonesia—pada waktu yang sama, di ruang yang sama—telah berakhir. Ia hanya muncul ketika kita teringat, suatu Minggu pagi, bahwa televisi pernah menyala dengan cara yang berbeda.
Mungkin, saat Doraemon tak lagi hadir di layar kaca, satu-satunya cara untuk menemuinya kembali adalah membuka halaman-halaman komik yang dulu pernah kita baca—atau belum sempat kita miliki.
Komik Doraemon tidak bergerak. Ia tidak bersuara. Namun justru di sanalah waktu melambat. Kita membaca dengan ritme sendiri, berhenti di panel-panel kecil, dan menemukan kembali cerita yang pernah menemani masa kanak-kanak—kini dengan pemahaman yang berbeda. Bagi sebagian orang, membaca ulang Doraemon bukan soal nostalgia semata, melainkan cara berdamai dengan masa kecil yang telah lewat, dan mengenalkannya kembali kepada generasi berikutnya—tanpa harus menunggu Minggu pagi.
Karena jika Doraemon telah pergi dari televisi, ia masih tinggal di buku.
Dan di sana, ia menunggu untuk dibuka kembali.